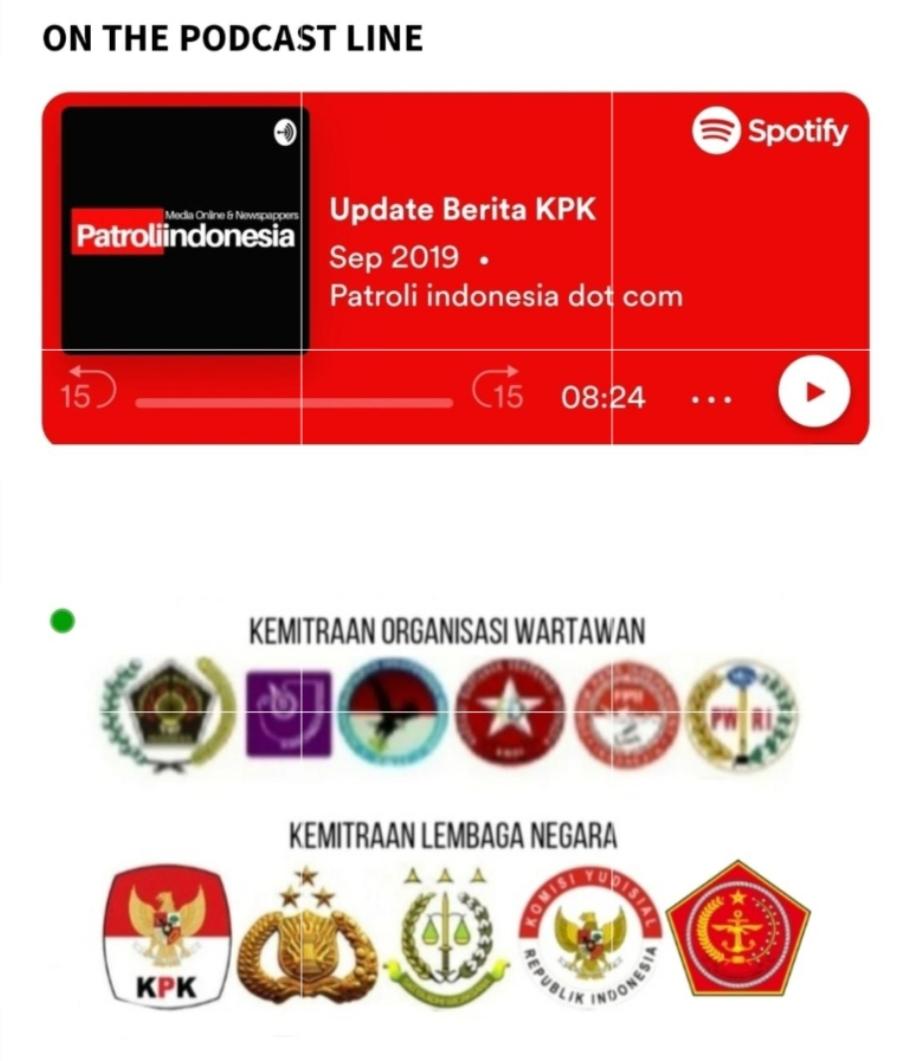Oleh: Burhan Ibnu Hazin
(Mahasiswa Program Doktor PAI UNU Surakarta, Carnival Cruise Ship Employee retirement USA).
Dalam dunia akademik, perbedaan pendapat sering kali menjadi medan ujian, bukan hanya bagi intelektualitas mahasiswa, tetapi juga bagi kebijaksanaan seorang dosen. Prof. KH. Amal Fathullah Zarkasyi, dosen Filsafat Islam ISID Gontor, adalah sosok yang bagi saya merepresentasikan kebijaksanaan itu secara nyata. Beliau adalah figur yang teguh dalam prinsip, tajam dalam argumentasi, namun lapang dalam menilai proses berpikir mahasiswanya.
Saya termasuk mahasiswa yang kerap berbeda pendapat dengan beliau, bahkan dalam isu-isu mendasar filsafat dan akidah. Namun, perbedaan itu tidak pernah berubah menjadi relasi yang kaku atau menegangkan secara personal. Justru sebaliknya, beliau tetap memberi ruang dialog yang sehat, menghargai keberanian berpikir, dan—yang mungkin jarang terjadi—tetap memberi nilai A, meskipun pandangan saya kerap berseberangan dengan beliau. Di situlah saya belajar bahwa objektivitas akademik tidak harus mengorbankan kedekatan humanis.
Salah satu momen yang paling membekas adalah perdebatan kami tentang bi‘tsah (kebangkitan). Saat itu saya berargumen dengan dalil ‘aqlī, bahwa kebangkitan tidak mungkin terjadi secara ruḥan wa jasadan ma‘an (ruh dan jasad sekaligus), mengingat jasad telah mengalami ikhtilāṭ al-ajsād bil-‘anāṣir al-arḍiyyah bercampurnya unsur-unsur tubuh dengan elemen tanah. Secara rasional, saya menilai kebangkitan jasadiah tidak lagi mungkin.
Namun, Ustadz Amal tidak mematahkan argumen panjang saya dengan uraian filosofis yang bertele-tele. Beliau hanya mengutip satu ayat dengan suara tenang namun menghunjam: “Qul man yuḥyil ‘iẓāma wa hiya ramīm.” (Katakanlah: siapa yang dapat menghidupkan tulang-belulang yang telah hancur?) Ayat yang sering kita baca seakan akan terlupakan dari ingatan kita. Singkat. Padat. Menggetarkan.
Pada saat itu saya, sebagai mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam, tersadar sepenuhnya bahwa akal memiliki batas, dan dalam persoalan metafisika, ‘aql harus tunduk di bawah naql. Bukan berarti akal dimatikan, tetapi diarahkan. Dan di situlah letak pendidikan sejati yang saya rasakan dari beliau: bukan memaksa setuju, tetapi mengarahkan kesadaran.
Menariknya, meskipun perdebatan kami kerap sengit dan tajam, hubungan saya dengan beliau tetap sangat akrab. Tidak ada jarak emosional, tidak ada dendam intelektual. Justru saya merasakan bahwa beliau sangat menghargai proses berpikir, bukan semata-mata hasil akhir. Beliau memahami bahwa mahasiswa adalah manusia yang sedang berada dalam fase pencarian, kegelisahan, dan menuju kematangan intelektual.
Ada satu kata yang hampir selalu beliau ucapkan dalam setiap diskusi kelas, terutama ketika perdebatan mulai mengeras dan argumen terasa terlalu dipaksakan: “qholat.” Kata itu terdengar sederhana, bahkan sekilas seperti penanda kekeliruan logika. Namun seiring waktu, saya menyadari bahwa “qholat” versi Ustadz Amal bukanlah vonis intelektual, melainkan peringatan metodologis.
Belakangan saya memahami bahwa kata “qholat” yang sering beliau lontarkan sejatinya merujuk pada pesan Al-Qur’an: “lā taghlū fī dīnikum” jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Dalam konteks filsafat dan akidah, yang beliau kritisi bukan keberanian berpikir, melainkan sikap melampaui batas: ketika akal dipaksa bekerja di wilayah yang bukan otoritasnya, atau ketika satu argumen ditarik terlalu jauh hingga kehilangan keseimbangan.
Dengan satu kata “qholat”, beliau seakan mengingatkan bahwa berpikir itu perlu keberanian, tetapi juga kerendahan hati epistemologis. Bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari argumentasi yang paling rumit, melainkan dari kemampuan menempatkan akal, wahyu, dan tradisi keilmuannya secara proporsional. Di titik inilah saya kembali belajar bahwa filsafat Islam bukan tentang ekstrem rasionalisme atau dogmatisme tekstual, melainkan tentang jalan tengah yang beradab.
Itulah kebesaran seorang pendidik sejati. Ustadz Amal Fathullah Zarkasyi mengajarkan saya bahwa filsafat bukan sekadar soal menang argumen, dan akidah bukan hanya hafalan dalil, melainkan perjalanan kesadaran. Dari beliau, saya belajar bahwa perbedaan pendapat bukan ancaman, tetapi sarana pembentukan kedewasaan berpikir asal dibimbing dengan hikmah.